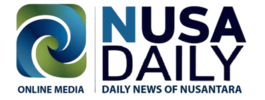Oleh: Noviardi Ferzi (Pengamat Politik dan Ekonomi)
JAMBI, NUSADAILY.ID – Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026 patut dibaca sebagai upaya serius keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Namun, target ini tidak boleh berhenti sebagai slogan optimisme. Ia hanya akan tercapai jika disertai keberanian melakukan pembedahan struktural secara mendalam di level mikro, wilayah kebijakan yang selama ini justru menjadi titik terlemah daya saing ekonomi nasional.
Stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini memang relatif solid. Inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen ±1 persen menjadi prasyarat penting untuk melindungi daya beli masyarakat yang menopang lebih dari separuh PDB. Namun, stabilitas harga hanyalah kondisi perlu, bukan kondisi cukup. Menjaga inflasi dan pangan tidak otomatis mengerek pertumbuhan ke level 6 persen. Akselerasi pertumbuhan membutuhkan kebijakan yang proaktif dan ofensif, bukan sekadar responsif terhadap gejolak jangka pendek.
Masalah mendasarnya terletak pada struktur investasi. Kontribusi investasi terhadap PDB masih bertahan di kisaran 24–25 persen, jauh di bawah ambang yang lazim dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan 6 persen. Pemerintah memang menargetkan lonjakan ke kisaran 31–32 persen PDB pada 2025–2026, dengan fokus pada sektor riil seperti manufaktur, energi, dan teknologi. Namun, kuantitas investasi semata tidak akan cukup jika tidak disertai peningkatan kualitas dan efisiensi modal.
Persoalan krusial lainnya terletak pada efisiensi investasi yang tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. ICOR pada dasarnya menjadi indikator apakah suatu perekonomian bekerja secara efisien atau justru boros kapital. Semakin rendah ICOR, semakin efisien investasi mendorong pertumbuhan; sebaliknya, ICOR yang tinggi menandakan bahwa pertumbuhan dicapai dengan biaya modal yang mahal.
Di sinilah persoalan ICOR menjadi krusial. Dengan ICOR di kisaran 6–6,3, Indonesia termasuk salah satu ekonomi paling boros kapital di Asia Tenggara, tertinggal dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang berada di kisaran 4,5–4,6. Artinya, setiap tambahan output membutuhkan investasi yang jauh lebih besar.
Menargetkan pertumbuhan 6 persen tanpa menurunkan ICOR mendekati angka 5 pada dasarnya adalah strategi yang mahal dan tidak berkelanjutan, membakar modal untuk hasil yang semakin marginal.
Karena itu, kebijakan investasi harus diarahkan pada penurunan biaya struktural, logistik yang mahal, energi yang tidak kompetitif, dan perizinan yang berlarut-larut. Percepatan pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki ICOR rendah (2–4) harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek simbolik.
Kawasan-kawasan ini harus berfungsi sebagai kantong efisiensi baru yang mampu menarik investasi produktif dan menciptakan nilai tambah tinggi. APBN pun harus menjalani reposisi strategis. Disiplin defisit memang penting untuk menjaga kepercayaan pasar, tetapi APBN tidak boleh terjebak sebagai instrumen proteksi sosial semata.
Tanpa peningkatan kualitas belanja pada infrastruktur logistik, energi, dan sumber daya manusia, APBN hanya akan menjadi pemadam kebakaran jangka pendek. Prinsip RAPBN 2026 “collect more, spending better” harus diterjemahkan secara konkret, belanja negara digeser dari belanja rutin dan subsidi konsumtif menuju investasi produktif yang benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Sinkronisasi dengan kebijakan moneter mutlak diperlukan agar dorongan fiskal tidak berhenti pada tekanan inflasi semata.
Titik krusial lainnya adalah melemahnya produktivitas industri pengolahan nonmigas. Kontribusinya terhadap PDB yang kini hanya sekitar 16–17 persen, turun dari hampir 20 persen pada awal 2010-an, merupakan sinyal jelas deindustrialisasi dini. Target Kementerian Perindustrian untuk mengembalikan kontribusi sektor ini ke sekitar 18,56 persen PDB pada 2026 harus dibaca sebagai agenda strategis nasional, bukan target sektoral semata.
Revitalisasi manufaktur tidak cukup dengan insentif fiskal. Ia menuntut infrastruktur yang andal, energi murah dan berkelanjutan, serta integrasi yang lebih dalam dengan rantai pasok global, khususnya pada subsektor logam dasar, kimia, makanan-minuman, dan farmasi. Tanpa kebangkitan manufaktur, pertumbuhan 6 persen akan terus bertumpu pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah, dua pilar yang sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
UMKM, meski menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, juga menghadapi tantangan struktural. Dengan sekitar 64–65 juta unit usaha yang menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60 persen PDB, masalah utama UMKM bukan skala, melainkan produktivitas. Membiarkan UMKM terjebak dalam ekonomi subsisten berarti membiarkan potensi pertumbuhan tereduksi. UMKM harus diintegrasikan ke dalam rantai pasok industri modern melalui digitalisasi, akses pembiayaan yang efektif, dan penguatan klaster industri agar dapat berkontribusi pada ekspor dan nilai tambah tinggi.
Pada akhirnya, pertumbuhan 6 persen di 2026 adalah ujian keberanian reformasi. Disiplin makro tanpa keberanian mikro hanya akan menghasilkan stabilitas yang stagnan. Reformasi mikro yang tak bisa ditawar mencakup penurunan biaya berusaha, deregulasi yang konsisten, revitalisasi manufaktur hingga produk akhir, serta transformasi UMKM yang terhubung dengan pendidikan vokasi dan kebutuhan sektor riil.
Tanpa reformasi struktural yang radikal di level mikro, target 6 persen akan tetap menjadi angka di atas kertas. Namun, dengan kombinasi disiplin makro dan keberanian mikro, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi kompetisi global.
Redaksi nusadaily.id/*