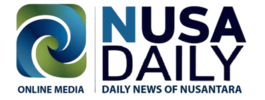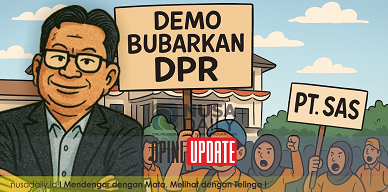Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
JAMBI, NUSADAILY.ID – Pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) oleh PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di wilayah Kota Jambi tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas bisnis biasa. Di balik deretan alat berat dan papan proyek yang berdiri, ada persoalan besar: soal ruang hidup masyarakat, lingkungan yang terancam, serta rasa keadilan yang dipertaruhkan. Bila PT. SAS terus berjalan tanpa menghormati suara rakyat, jangan salahkan bila gelombang perlawanan akan bangkit, sebagaimana yang telah diperlihatkan rakyat Indonesia ketika turun menuntut pembubaran DPR, ataupun ribuan massa yang mengepung gedung DPRD Provinsi Jambi dalam demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
Demonstrasi di DPRD Jambi bukan sekadar letupan emosional, melainkan cerminan akumulasi kekecewaan. Warga turun ke jalan bukan karena ingin gaduh, melainkan karena merasa aspirasi mereka diabaikan dan keputusan-keputusan politik justru berpihak pada segelintir kepentingan. Di titik itulah, teori Relative Deprivation dari Ted Robert Gurr (1970) menemukan relevansinya: perlawanan lahir dari kesenjangan antara harapan dan realitas. Masyarakat berharap pembangunan memberi kesejahteraan, tetapi yang mereka rasakan justru ancaman polusi, rusaknya lingkungan, serta ketidakpastian nasib ekonomi.
Lebih jauh, teori Resource Mobilization (McCarthy & Zald, 1977) menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika warga mampu mengorganisir diri, memanfaatkan jaringan, dan mengonsolidasi sumber daya. Kita bisa melihat bagaimana ribuan masyarakat Jambi memadati gedung DPRD dengan spanduk, orasi, dan solidaritas yang terjalin lintas kelompok. Itu adalah tanda bahwa infrastruktur sosial untuk perlawanan sudah terbentuk. Jika PT. SAS tetap keras kepala, bukan tidak mungkin infrastruktur sosial itu akan kembali bekerja, kali ini dengan sasaran yang lebih terarah: proyek mereka.
Tak bisa dipungkiri, setiap pembangunan yang menyingkirkan partisipasi rakyat selalu meninggalkan bara konflik. Tarrow (1998) dalam Power in Movement menegaskan bahwa aksi massa lahir bukan semata karena provokasi, tetapi karena terbukanya ruang peluang politik ketika negara dianggap gagal mengawal kepentingan rakyat. Jambi sedang menuju fase itu. Ketika aparat dan lembaga negara tampak lemah, atau malah cenderung berpihak pada modal besar, rakyat mengambil alih panggung politik di jalanan. Demonstrasi di DPRD Jambi adalah alarm keras yang mestinya membuat PT. SAS berhitung ulang.
Riset lokal memperkuat tesis ini. Prayogo (2021) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri yang minim transparansi dan keterlibatan publik hampir selalu berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Dalam kasus PT. SAS, bukan hanya potensi kerusakan lingkungan yang menjadi masalah, melainkan juga psikologi sosial: rakyat merasa dipinggirkan di tanah mereka sendiri. Itu adalah pemantik utama lahirnya distrust, dan distrust yang mengeras akan menjelma menjadi perlawanan.
Sejarah politik Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bahwa rakyat yang kecewa mampu mengguncang bangunan kekuasaan. Dari reformasi 1998, gelombang aksi menolak UU Cipta Kerja, hingga demonstrasi di DPRD Jambi yang terakhir, semuanya lahir dari satu akar yang sama: pengkhianatan terhadap rasa keadilan. Jika PT. SAS berpikir bahwa rakyat akan diam, mereka lupa bahwa jalanan di negeri ini telah lama menjadi arena perlawanan rakyat terhadap tirani politik maupun ekonomi.
PT. SAS masih punya kesempatan untuk mengubah arah, berdialog dengan masyarakat, dan membangun proyeknya di atas dasar keterbukaan dan keadilan. Tetapi bila kesempatan ini diabaikan, maka sejarah perlawanan rakyat yang penuh energi dan daya ledak akan kembali berulang. Bedanya, kali ini rakyat tidak berhadapan dengan institusi politik, melainkan dengan korporasi yang memunggungi mereka. Dan bila itu terjadi, jangan salahkan bila PT. SAS akan menghadapi gelombang besar yang tidak bisa dihentikan dengan sekadar pagar proyek atau aparat bersenjata.
Daftar Pustaka
Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. Princeton University Press.
McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1241.
Prayogo, D. (2021). Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 235–250. Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.