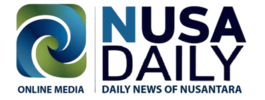Oleh: Dr. Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
(Peneliti SDGs Center / Dosen IAKSS / Advokat Peradi)
Seperti dikatakan Francis Fukuyama (2014), “Democracy is not only about elections; it is about accountability and the rule of law.” Jika demokrasi hanya dipahami sebagai pemilu tanpa akuntabilitas dan supremasi hukum, maka relevansinya menjadi semu.
BUNGO, NUSADAILY.ID – Sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia menahbiskan diri sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Reformasi politik melahirkan kebebasan sipil, pemilu yang relatif kompetitif, dan penguatan institusi demokrasi. Namun, dua dekade lebih berlalu, kita perlu mengajukan pertanyaan fundamental: apakah sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini masih relevan dengan kondisi sekarang? Pertanyaan ini bukan sekadar refleksi historis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak mengingat gejala demokrasi yang semakin mengalami defisit kualitas.
Demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan sebuah proses yang terus beradaptasi. Larry Diamond menegaskan, “Democracy is not a destination, but a journey that requires continuous nurturing” (Diamond, 1999). Artinya, demokrasi harus selalu diuji relevansinya terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Jika tidak, demokrasi hanya menjadi ritual prosedural tanpa makna substantif.
Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi kita mengacu pada model demokrasi konstitusional, yang menggabungkan elemen pemilu langsung, checks and balances, dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut Robert A. Dahl (1989), demokrasi modern (polyarchy) memiliki dua dimensi: partisipasi politik yang luas dan kompetisi politik yang terbuka. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah dua dimensi ini benar-benar berjalan optimal di Indonesia? Jika partisipasi politik hanya menjadi formalitas dan kompetisi politik dibajak oleh oligarki, maka demokrasi kehilangan makna substantifnya.
Indonesia secara formal memenuhi indikator demokrasi prosedural: pemilu langsung, multipartai, kebebasan berpendapat, dan desentralisasi. Bahkan, laporan The Economist Intelligence Unit (2023) masih menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat), bukan rezim otoritarian. Namun, status flawed ini mengisyaratkan ada persoalan serius yang menggerus kualitas demokrasi kita.
Tantangan Demokrasi Indonesia
Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi empat tantangan utama:
- Oligarki Politik dan Politik Uang
Demokrasi idealnya menjamin kedaulatan rakyat. Namun, realitas menunjukkan bahwa demokrasi kita cenderung menjadi arena transaksi antara elite politik dan pemodal besar. Jeffrey Winters (2011) menyebut fenomena ini sebagai oligarchic capture, di mana kekuatan modal mengendalikan kekuasaan politik. Biaya politik yang sangat tinggi membuat partisipasi politik rakyat biasa hanya sebatas memilih, sementara pengambilan keputusan dikuasai oleh segelintir elite. - Komersialisasi Pemilu
Pemilu yang seharusnya menjadi instrumen kompetisi ide dan program kini lebih menyerupai ajang kompetisi modal. Money politics bukan lagi rahasia, melainkan budaya. Ini membuat demokrasi menjadi prosedur yang mahal dan cenderung melahirkan pemimpin pragmatis, bukan visioner. - Polarisasi dan Politik Identitas
Fenomena identity politics yang semakin menguat sejak Pilpres 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa demokrasi kita rentan ditunggangi isu SARA. Alih-alih memperkuat kohesi sosial, demokrasi justru memicu perpecahan. Seperti yang diingatkan Mietzner (2020), “Indonesia’s democracy is not collapsing, but it is under severe strain from polarization and elite manipulation.” - Disinformasi dan Manipulasi Digital
Era demokrasi digital membawa tantangan baru: banjir informasi yang tidak selalu akurat. Hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi opini melalui media sosial menjadi instrumen politik yang efektif namun berbahaya. Demokrasi berbasis informasi berubah menjadi demokrasi berbasis disinformasi.
Relevansi Demokrasi Indonesia
Pertanyaan utama: apakah demokrasi Indonesia masih relevan dengan kondisi sekarang? Jawabannya: ya, tetapi dengan catatan besar. Demokrasi tetap relevan karena demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang partisipasi rakyat, menjamin kebebasan sipil, dan membatasi kekuasaan melalui konstitusi. Alternatif seperti otoritarianisme bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebebasan.
Namun, relevansi ini bersifat formal, bukan substantif. Demokrasi kita hari ini lebih banyak berwujud prosedural: rakyat diberi kedaulatan setiap lima tahun melalui pemilu, tetapi setelah itu, kebijakan publik dikuasai oleh elite politik dan kepentingan oligarki. Dengan kata lain, demokrasi kita tengah mengalami krisis substansi.
Seperti dikatakan Francis Fukuyama (2014), “Democracy is not only about elections; it is about accountability and the rule of law.” Jika demokrasi hanya dipahami sebagai pemilu tanpa akuntabilitas dan supremasi hukum, maka relevansinya menjadi semu.
Jalan Perbaikan
Agar demokrasi Indonesia tidak sekadar bertahan secara prosedural, perlu ada reformasi mendasar, yaitu penguatan demokrasi substantif. Demokrasi harus menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan.
Langkah yang diperlukan antara lain:
- Literasi politik yang kuat dan pendidikan kewarganegaraan yang membentuk warga kritis, bukan pragmatis.
- Reformasi sistem kepartaian dan pembiayaan politik, termasuk transparansi dana kampanye. Skema public funding untuk partai politik dapat mengurangi ketergantungan pada pemodal besar.
- Revitalisasi lembaga penegak hukum, khususnya independensi KPK dan lembaga yudisial, agar mampu menahan laju korupsi politik yang merusak fondasi demokrasi.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk e-voting, keterbukaan data, dan pengawasan publik.
Sistem demokrasi Indonesia saat ini masih relevan, tetapi dalam kondisi rapuh dan penuh ancaman. Relevansi ini harus dipertahankan melalui penguatan demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural. Demokrasi harus menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, memperkuat supremasi hukum, dan memastikan kedaulatan rakyat berjalan nyata, bukan simbolik.
Sebagaimana pesan Soekarno: “Demokrasi kita harus berkepribadian Indonesia. Bukan demokrasi Barat yang hanya bicara suara terbanyak, tapi demokrasi yang berakar pada gotong-royong dan keadilan sosial.”
Pesan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada angka suara, tetapi harus menyejahterakan seluruh rakyat.
Kesimpulan
Jika demokrasi masih relevan, mengapa kualitasnya sering dipertanyakan? Jawabannya terletak pada implementasi. Demokrasi kita berjalan secara prosedural, tetapi gagal mencapai substansi.
Prinsip demokrasi mengandaikan kesetaraan partisipasi politik. Namun, kenyataannya politik Indonesia dibajak oleh kekuatan modal. Biaya politik yang sangat tinggi membuat kompetisi politik tidak setara. Jeffrey Winters (2011) menyebut kondisi ini sebagai oligarchic capture, situasi di mana oligarki mengendalikan proses politik. Akibatnya, rakyat memang memilih, tetapi tidak menentukan arah kebijakan.
Demokrasi juga rentan dipolitisasi identitas. Pemilu berubah menjadi ajang mobilisasi identitas primordial, memperkuat polarisasi, dan mengikis kohesi sosial. Selain itu, supremasi hukum masih lemah, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik, seperti dalam revisi UU KPK (2019).
Era digital pun menghadirkan paradoks: membuka ruang partisipasi sekaligus memperbesar risiko disinformasi.
Akar masalahnya terletak pada tiga hal:
- Budaya politik yang belum matang (civic culture yang lemah, pragmatisme, patronase).
- Desain institusi yang tidak kokoh (fragmentasi partai dan koalisi pragmatis).
- Lemahnya regulasi pembiayaan politik.
Apakah solusinya mengganti sistem? Jawabannya tidak. Masalah kita bukan pada desain normatif, melainkan kualitas implementasi. Demokrasi tetap relevan, tetapi harus diperbaiki. Seperti ditegaskan Fukuyama (2014), “The challenge for democracy today is not to defend its principles, but to improve its performance.” Tantangannya bukan mengganti demokrasi, tetapi memastikan ia bekerja sesuai prinsipnya.
Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus diperkuat melalui literasi politik, reformasi partai dan pembiayaan politik, independensi hukum, serta pengelolaan ruang digital yang sehat. Hanya dengan begitu, demokrasi akan benar-benar menjadi mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif, bukan sekadar ritual prosedural.
Redaksi nusadaily.id/*