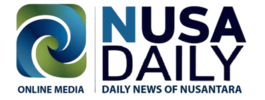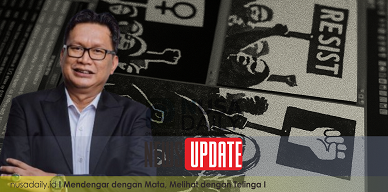Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
JAMBI, NUSADAILY.ID – Pandangan yang menyederhanakan demonstrasi anarkis hanya sebagai ancaman investasi dan biaya sosial adalah reduksi yang menyesatkan. Kerangka teori biaya transaksi (Coase, Williamson) maupun conflict trap (Collier & Hoeffler) kerap digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian sosial semata-mata dalam logika ekonomi. Namun, mengimpor konsep ini ke dalam konteks demonstrasi di Jambi adalah kekeliruan fundamental.
Aksi massa di jalanan bukanlah gejala “inefisiensi pasar” atau “lingkaran setan konflik”, melainkan ekspresi politik rakyat yang kecewa atas kegagalan negara menghadirkan keadilan.
Dalam kerangka biaya transaksi, konflik dianggap sebagai “distorsi” yang menambah ongkos pertukaran dan mengganggu efisiensi pasar. Logika ini menempatkan masyarakat hanya sebagai variabel pengganggu arus modal. Padahal, kemarahan rakyat di Jambi lahir dari persoalan struktural: APBD yang tidak berpihak, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara, dan konflik agraria yang dibiarkan berlarut. Menyebut semua itu sekadar “biaya” adalah bentuk reduksi yang menihilkan dimensi moral dan politik dari perlawanan.
Pengalaman global juga menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Di Amerika Latin, protes petani di Bolivia terhadap privatisasi air (Cochabamba Water War, 2000) tidak bisa dipahami sekadar sebagai peningkatan biaya transaksi bagi investor asing. Aksi tersebut lahir dari klaim rakyat atas hak dasar, menolak ketika kebutuhan hidup diprivatisasi. Artinya, logika ekonomi gagal menangkap makna sosial dari protes.
Teori perangkap konflik menekankan bahwa kekerasan sosial berulang menciptakan siklus instabilitas yang sulit diputus. Akan tetapi, model ini lebih tepat untuk menjelaskan perang saudara atau konflik etnis berkepanjangan. Di Jambi, demonstrasi anarkis tidak lahir dari etnisitas atau balas dendam historis, melainkan dari frustrasi publik terhadap tata kelola pemerintahan yang koruptif dan keberpihakan yang timpang. Dengan menggunakan kerangka ini, rakyat distigma sebagai ancaman, sementara akar masalah struktural yakni politik pro modal dan abainya pemerintah, dibiarkan tak tersentuh.
Sebagai perbandingan, teori conflict trap juga terbukti gagal menjelaskan protes massa di Tunisia (Arab Spring, 2011). Aksi-aksi itu tidak mengulang siklus konflik lama, melainkan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap otoritarianisme, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi. Sama seperti di Jambi, penyebabnya lebih bersifat struktural dan politis, bukan konflik horizontal yang diwariskan.
Alih-alih terjebak dalam paradigma ekonomi sempit, gerakan sosial di Jambi lebih tepat dipahami melalui kerangka Charles Tilly, Sidney Tarrow, atau Ted Robert Gurr. Dalam analisisnya Tarrow menekankan bahwa aksi kolektif lahir dari political opportunity structure, yaitu terbukanya ruang politik bagi mobilisasi. Protes di Jambi mencuat karena pemerintah gagal menyalurkan aspirasi publik, sehingga jalanan menjadi arena alternatif untuk menyuarakan tuntutan. Sedangkan Gurr menjelaskan fenomena ini dengan konsep relative deprivation. Ketika masyarakat merasa jurang antara harapan dan kenyataan kian melebar, misalnya janji kesejahteraan yang tidak terwujud, sementara kerugian akibat tambang makin nyata, maka potensi aksi protes meningkat drastis.
Pengalaman di Afrika Selatan pasca-apartheid juga relevan. Protes komunitas miskin di Johannesburg terkait layanan dasar tidak bisa dilihat sekadar sebagai “destabilisasi” atau “konflik berulang”. Justru, ia merupakan artikulasi ketidakpuasan terhadap janji demokrasi yang tidak ditepati. Perspektif gerakan sosial memungkinkan kita memahami hal serupa di Jambi, bahwa demonstrasi adalah ekspresi politik warga negara, bukan sekadar hambatan ekonomi.
Mengandalkan seloko dan adat Melayu Jambi sebagai “rem sosial” juga merupakan bentuk simplifikasi. Kearifan lokal hanya dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial bila didukung oleh keteladanan moral pemimpin. Tanpa itu, seloko hanya menjadi retorika kultural yang digunakan untuk menutupi defisit kepemimpinan. Perbandingan dengan Bali melalui Tri Hita Karana tidak relevan, sebab di sana kearifan lokal berjalan beriringan dengan distribusi manfaat ekonomi yang nyata, bukan sekadar simbol.
Lalu, tingginya realisasi investasi di Jambi tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan rakyat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (2023) menunjukkan Jambi termasuk provinsi dengan konflik agraria tertinggi. Walhi Jambi (2024) juga melaporkan banjir berulang di Batanghari dan Muaro Jambi yang dipicu oleh aktivitas tambang batubara. Dengan demikian, investasi justru menjadi sumber keresahan sosial, bukan jaminan kemakmuran.
Mengidentikkan stabilitas dengan absennya protes adalah bentuk kesesatan berpikir. Stabilitas sejati lahir dari partisipasi rakyat, transparansi kebijakan, dan keadilan distribusi. Menekan demonstrasi demi menjaga iklim investasi hanya menciptakan stabilitas semu. Investor yang serius justru lebih menghargai demokrasi yang sehat dan tata kelola yang transparan dibanding represi sosial yang rapuh.
Membaca demonstrasi anarkis dengan kacamata teori biaya transaksi dan conflict trap adalah kekeliruan konseptual. Keduanya gagal menjelaskan dimensi politik, kultural, dan ekologis yang melatari keresahan rakyat Jambi. Sebaliknya, teori gerakan sosial dan pengalaman global menunjukkan bahwa demonstrasi adalah konsekuensi logis dari kekecewaan publik terhadap tata kelola negara. Yang diperlukan bukan tameng budaya atau logika ekonomi sempit, melainkan keberanian politik untuk membangun keadilan sosial yang sesungguhnya.
Daftar Pustaka
Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386–405.
Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595.
Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press.
Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.
Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. Journal of Democracy, 29(4), 104–118.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria. Jakarta: KPA.
WALHI Jambi. (2024). Laporan Lingkungan: Dampak Tambang Batubara terhadap Ekosistem dan Masyarakat Jambi. Jambi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Roberts, A. (2011). The Logic of Discipline: Global Capitalism and the Architecture of Government. Oxford: Oxford University Press.
Spronk, S. (2007). Roots of Resistance to Urban Water Privatization in Bolivia: The “New Working Class,” the Crisis of Neoliberalism, and Public Services. International Labor and Working-Class History, 71(1), 8–28.
Beinin, J., & Vairel, F. (Eds.). (2013). Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford: Stanford University Press. Bond, P. (2014). Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa. London: Pluto Press.