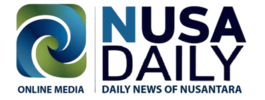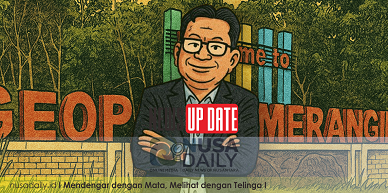Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
JAMBI, NUSADAILY.ID – Pengukuhan Merangin sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 2023 digadang-gadang sebagai pencapaian monumental. Dengan kekayaan fosil tumbuhan berusia 300 juta tahun yang tersimpan dalam formasi batuan Karbon-Permian, kawasan ini menjadi satu-satunya di Asia Tenggara dan memiliki nilai ilmiah tinggi dalam studi geologi (Jambi Independent, 2025).
Namun setelah euforia itu mereda, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana status internasional ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar? Apakah pengakuan UNESCO telah membawa perubahan sosial-ekonomi yang berarti, atau hanya menjadi simbol prestise global yang menutupi persoalan riil di tingkat lokal?
Secara formal, penetapan geopark memang menempatkan Merangin dalam peta dunia geologi. Tetapi manfaat konkret bagi warga sekitar masih jauh dari harapan. Studi UNESCO (2024) bahkan menegaskan bahwa sebagian besar geopark di dunia menghadapi tantangan serupa: rendahnya pelibatan masyarakat dan belum meratanya manfaat ekonomi. Artinya, status UGGp tidak serta merta menjamin kesejahteraan.
Data kunjungan wisata pun menunjukkan paradoks serupa. Tahun 2023, jumlah wisatawan ke Merangin tercatat mencapai 463.552 orang, menempatkan kabupaten ini sebagai tujuan wisata nomor dua di Provinsi Jambi (ANTARA News Jambi, 2024). Namun, sebagian besar kunjungan hanya bersifat transit, karena Merangin berada di jalur lintas antarprovinsi. Tingginya angka wisatawan tidak sepenuhnya mencerminkan daya tarik Geopark Merangin, melainkan faktor geografis. Dengan demikian, dampak ekonomi dari status geopark terhadap masyarakat lokal belum signifikan.
Penelitian Ramdani (2023) juga menegaskan bahwa citra destinasi dan buruknya aksesibilitas menjadi kendala serius pengembangan pariwisata berbasis geopark. Kawasan seluas 4.832 km² dengan potensi luar biasa itu masih belum tergarap optimal karena keterbatasan infrastruktur, promosi, dan layanan wisata.
Masalah kelembagaan juga tidak kalah penting. Fakta bahwa pengelolaan kawasan sebesar dan sekompleks ini hanya ditangani oleh sembilan staf menunjukkan lemahnya kapasitas institusional. UNESCO (2024) bahkan menyoroti keterbatasan staf, anggaran, dan koordinasi antar lembaga sebagai masalah umum di banyak geopark. Alih-alih menjadi motor penguatan konservasi, kondisi ini justru berpotensi menjadikan geopark sekadar legitimasi simbolis, sementara kerusakan ekologis dan ketidakadilan ekonomi tetap berlangsung.
Kondisi ini bukan hanya terjadi di Merangin. Studi Susanti et al. (2023) tentang Geopark Gunung Sewu memperlihatkan bahwa pengakuan UNESCO tidak otomatis menjamin konservasi efektif. Lemahnya koordinasi antaraktor dan keterbatasan dana menjadi hambatan serius. Merangin menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi dengan maraknya tambang emas ilegal, deforestasi sawit, serta ekspansi batubara. Situasi ini membuat efektivitas pengelolaan geopark semakin diragukan.
Sudah dua tahun sejak pengakuan UNESCO, capaian nyata masih terbatas. Kajian UIR (2024) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat hanya sebatas wacana. Desa-desa di sekitar kawasan masih terjebak dalam pola ekonomi ekstraktif. Penelitian Wibowo (2020) menegaskan bahwa manfaat ekonomi hanya dinikmati lingkaran kecil, dan belum menjadi alternatif nyata bagi masyarakat yang hidup dari tambang maupun perkebunan sawit.
Fenomena ini sejalan dengan studi perbandingan geopark di Asia (Ng et al., 2021) yang menekankan bahwa ketimpangan distribusi manfaat merupakan masalah berulang, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, peran UNESCO seharusnya tidak berhenti pada pemberian label internasional, tetapi juga sebagai fasilitator penguatan kapasitas lokal dan pengawas implementasi.
Di balik slogan “memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat”, realitas di lapangan menunjukkan kontras. Warga di sekitar kawasan geopark masih hidup dalam kondisi marginal: infrastruktur desa tertinggal, akses pendidikan terbatas, dan konflik agraria dengan industri ekstraktif tetap berlangsung. Penelitian Ramdani (2023) bahkan menunjukkan rendahnya partisipasi warga akibat lemahnya integrasi suara lokal dalam tata kelola. Program ekowisata yang digadang-gadang pun sering gagal berkelanjutan karena minimnya pendampingan teknis dan akses pasar.
Geopark Merangin pada akhirnya lebih banyak berfungsi sebagai panggung simbolisme global ketimbang solusi nyata bagi masyarakat lokal. Manfaat ekonomi tidak merata, kelembagaannya rapuh, dan capaian riilnya minim, sementara masyarakat tetap menjadi penonton.
Jika pemerintah daerah dan badan pengelola serius ingin menghadirkan perubahan, paradigma harus digeser dari sekadar pencitraan internasional menuju agenda nyata. Kapasitas kelembagaan harus diperkuat, partisipasi masyarakat diperluas, dan skema distribusi manfaat dirancang lebih adil. Tanpa langkah konkret ini, Geopark Merangin hanya akan dikenang sebagai “mercusuar prestise” yang gagal menerangi lingkungannya sendiri.
Pemerhati Kebijakan Publik
Daftar Pustaka
ANTARA News Jambi. (2024). Pemerintah Kabupaten Merangin dorong kunjungan wisata dan bentuk Barista. https://jambi.antaranews.com
Jambi Independent. (2025, 10 Juli). Pesona Geopark Merangin: Jejak sejarah bumi yang tersembunyi di Jambi. https://jambiindependent.disway.id/read/701872/pesona-geopark-merangin-jejak-sejarah-bumi-yang-tersembunyi-di-jambi
Ng, Y. C., et al. (2021). Economic impact of UNESCO global geoparks on local communities in Asia. Journal of Environmental Management, 281, 111850.
Ramdani, D. (2023). Analisis Keputusan Berkunjung melalui Minat Berkunjung, Citra Destinasi, dan Aksesibilitas pada Geopark Merangin Jambi. ResearchGate.
Susanti, R., et al. (2023). A Case Study in Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, Indonesia. Sustainability, 15(17), 6707.
UNESCO. (2024). Survey on Global Geoparks Engagement with Local Communities. Paris: UNESCO Secretariat.
Wibowo, S. (2020). Pengaruh Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Merangin terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Batu. ResearchGate. UIR. (2024). The Hope Preservation of Geodiversity and Culture of Merangin Jambi. Journal of Regional Planning Studies.