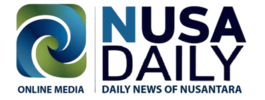Oleh: Asra’i Maros, S.Sos., M.Si. (Peneliti SDGs Center/Dosen IAKSS)
BUNGO, NUSADAILY.ID – Kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 digadang-gadang sebagai solusi bagi tenaga honorer yang selama ini berada dalam posisi serba tidak pasti. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai jalan tengah yang memungkinkan tenaga honorer mendapat status Aparatur Sipil Negara (ASN), meski dengan jam kerja dan upah yang menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Namun, harapan yang ditawarkan kebijakan ini ternyata tidak sepenuhnya bisa diharap, sebab realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal.
Secara normatif, PPPK paruh waktu berstatus ASN dengan masa kerja satu tahun yang dapat diperpanjang, dan gaji minimal ditetapkan setara dengan penghasilan ketika masih menjadi tenaga honorer atau paling tidak mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) daerah. Pada kertas kebijakan, ini tampak sebagai bentuk pengakuan formal atas jasa tenaga honorer yang selama ini menopang layanan publik. Namun, di sejumlah daerah, implementasi aturan ini justru menimbulkan keresahan. Salah satu contohnya muncul di Kabupaten Bungo, Jambi, di mana beredar isu bahwa penghasilan PPPK paruh waktu hanya akan setara dengan honorer, berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Angka ini jauh di bawah UMR dan tentu tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup layak (Antara Jambi, 2023).
Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3.234.535 per bulan, dan bahkan di Kota Jambi UMR mencapai Rp3.607.223 (Kompas.com, 2 Februari 2025; Kumparan.com, 2025). Kontras ini memperlihatkan betapa jauh ketimpangan antara standar minimum penghidupan yang diakui negara dengan kenyataan penghasilan honorer atau PPPK paruh waktu di daerah. Dengan gaji Rp700 ribu hingga Rp1 juta, mereka bahkan hanya menerima sekitar 20–30 persen dari standar minimum yang berlaku.
Fenomena di Bungo juga memperlihatkan celah besar dari kebijakan PPPK paruh waktu. Regulasi yang hanya menyebut “setara penghasilan sebelumnya atau sesuai UMR” menyisakan ruang interpretasi luas bagi pemerintah daerah. Alih-alih menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan, skema ini bisa berubah menjadi sekadar legalisasi pekerjaan bergaji rendah dengan label ASN. Tidak adanya kepastian mengenai formula penghitung gaji membuat posisi pekerja menjadi sangat rentan. Mereka bisa saja mendapat penghasilan yang tidak jauh berbeda, bahkan lebih rendah dari ekspektasi, meskipun statusnya sudah berganti menjadi ASN.
Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah mengusung narasi bahwa skema PPPK paruh waktu memberi harapan baru bagi tenaga honorer. Di sisi lain, tanpa standar penghasilan yang jelas dan terukur, kebijakan ini justru menjerumuskan para pekerja ke dalam lingkaran kemiskinan yang dilegalkan oleh negara. Janji status ASN kehilangan makna ketika penghasilan yang diterima tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup.
Lebih jauh, kontrak yang hanya berlaku satu tahun dan bergantung pada evaluasi kinerja juga menambah lapisan ketidakpastian. Bagi tenaga kerja yang sudah lama mengabdi, hal ini justru memperpanjang bayang-bayang ketidakjelasan. Tidak ada jaminan mobilitas karier, tidak ada kepastian peningkatan kesejahteraan, dan tidak ada instrumen yang memastikan bahwa tenaga paruh waktu akan memiliki jalur konversi ke PPPK penuh waktu atau CPNS (Kompas TV, 2025). Akibatnya, status ASN paruh waktu hanya sekadar simbol tanpa substansi.
Kebijakan publik seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara. Namun, bila implementasi PPPK paruh waktu dibiarkan tanpa pengaturan teknis yang jelas, maka yang terjadi hanyalah lahirnya kelas baru dalam birokrasi: ASN dengan hak dan penghasilan minimalis, terjebak dalam pekerjaan temporer yang dilegalkan oleh negara. Harapan untuk mendapat kepastian justru berubah menjadi beban baru yang mengekalkan kerentanan sosial ekonomi.
Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kebijakan ini sungguh memberi harapan atau justru sekadar fatamorgana? Bila gaji hanya setara Rp700 ribu hingga Rp1 juta, sebagaimana isu di Bungo, maka PPPK paruh waktu hanya akan menjadi contoh nyata dari sebuah kebijakan yang melahirkan harapan yang tak bisa diharap. Solusi yang ditawarkan pemerintah akhirnya kehilangan makna karena gagal menjawab kebutuhan dasar: kesejahteraan dan kepastian hidup layak bagi mereka yang sudah lama mengabdi pada negara.
Redaksi nusadaily.id/*