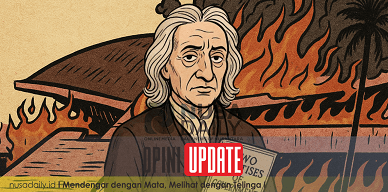Oleh: Dr. Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
(Peneliti SDGs Center / Dosen IAKSS / Advokat Peradi)
"Jika janji adalah jembatan antara kuasa dan nurani, mengapa kini yang tersisa hanya reruntuhan?"
Pertanyaan itu menggema di hati rakyat ketika suara mereka, yang seharusnya menjadi fondasi negara, tak lagi digubris. Demokrasi lahir dari keyakinan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Para wakil rakyat, termasuk mereka yang duduk di parlemen, bukanlah penguasa, melainkan penerima amanah. Namun, ketika amanah berubah menjadi alat memperkaya diri, ketika kebijakan lebih berpihak pada oligarki daripada pada rakyat banyak, maka kontrak sosial yang menjadi dasar bernegara mengalami retakan serius.
Fenomena seruan “Bubarkan DPR” yang ramai di ruang publik bukanlah luapan emosi sesaat. Ia adalah tanda luka mendalam pada relasi antara rakyat dan wakilnya. John Locke, dalam Two Treatises of Government, menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak ilahi yang turun dari langit, melainkan hasil kesepakatan rakyat. Dan setiap kesepakatan dapat dicabut jika dikhianati.
Locke percaya manusia pada mulanya hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Namun kebebasan itu rapuh, ancaman kekacauan mendorong manusia membentuk kontrak sosial: menyerahkan sebagian hak alami kepada negara demi hidup yang lebih aman, adil, dan tertib. Tapi kontrak ini bukan tanpa syarat. Ia hanya sah jika pemerintah menjaga kehidupan, kebebasan, dan harta rakyat; jika lembaga politik membuat hukum demi kepentingan bersama, bukan untuk segelintir orang.
Ketika syarat itu diabaikan, kontrak sosial kehilangan legitimasi. Saat itulah rakyat berhak menggugat kekuasaan. Locke bahkan menyebut perlawanan terhadap tirani sebagai hak kodrati. “Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Amanah dapat dicabut ketika ia ternoda oleh pengkhianatan.”
Di Indonesia, DPR seharusnya menjadi wajah kedaulatan rakyat. Namun berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik kerap berada di titik rendah. Kasus korupsi, transaksi politik anggaran, dan lahirnya undang-undang kontroversial (seperti revisi UU KPK, UU Minerba, hingga wacana perpanjangan masa jabatan) melahirkan satu pertanyaan getir: Apakah DPR masih rumah rakyat, atau sudah menjelma istana oligarki?
Rakyat merasa dikhianati ketika keputusan parlemen lebih menguntungkan elit ketimbang publik. Dari sinilah seruan “Bubarkan DPR” menemukan momentumnya. Bukan karena rakyat menolak demokrasi, tetapi justru karena mereka mencintai demokrasi. Cinta itu kini terluka, sebab janji telah dikhianati. Demokrasi tidak mati ketika rakyat bersuara, ia justru mati ketika suara itu dibungkam.
Locke menolak absolutisme. Baginya, ketika pemerintah atau parlemen bertindak di luar mandat, mereka telah mengumumkan perang terhadap rakyat. Dalam keadaan demikian, rakyat tidak lagi terikat untuk taat. Mereka bebas mencabut mandat, mengganti penguasa, bahkan merombak sistem. Maka, jika rakyat menuntut pembubaran DPR, itu bukanlah pengkhianatan, melainkan upaya mengembalikan kedaulatan kepada pemilik sejatinya.
Fenomena ini menyimpan dua kemungkinan besar bagi demokrasi Indonesia:
- Restorasi Kepercayaan
Jika jeritan rakyat dipahami sebagai kritik cinta, maka ini bisa menjadi momentum reformasi parlemen. Transparansi, etika politik, dan pembatasan oligarki dapat diperkuat. Kontrak sosial bisa dipulihkan, demokrasi bisa lahir kembali, lebih jujur, lebih bersih, lebih bermartabat. - Disintegrasi Legitimasi
Namun, jika tuntutan itu diabaikan, retaknya kontrak sosial bisa menjelma jurang. Ketidakpercayaan berubah menjadi apatisme, atau lebih parah: radikalisasi hingga chaos. Inilah titik paling berbahaya dalam pandangan Locke, saat rakyat merasa seluruh pintu legal tertutup, revolusi menjadi pilihan terakhir.
"Demokrasi sejati tidak takut pada kritik. Ia hanya gentar pada kebisuan yang lahir dari putus asa."
Karena itu, pemerintah dan DPR perlu segera merajut kembali kepercayaan publik. Kontrak sosial bukan sekadar teks konstitusi, melainkan ikatan moral yang hanya bisa dijaga dengan kejujuran.
Refleksi Puitis: Di Ujung Kontrak yang Rapuh
Di ruang parlemen yang megah, kata-kata seharusnya janji. Namun kini, ia menjelma bayangan, menari di atas kepentingan pribadi. Rakyat menatap dari kejauhan, bertanya lirih:
"Apakah suara kami hanya angka di kotak suara yang kau lupakan?"
Jika kontrak sosial adalah jembatan, kini tiangnya rapuh oleh kerakusan kuasa. Dan ketika jembatan itu hampir ambruk, salahkah bila rakyat mencari jalan lain untuk menyeberang?
Tuntutan membubarkan DPR bukanlah sikap anti-demokrasi. Ia adalah alarm keras atas runtuhnya legitimasi politik. Dalam pandangan Locke, kekuasaan adalah kontrak bersyarat; dan ketika kontrak itu diingkari, rakyat memiliki hak kodrati untuk menggugat.
Pada akhirnya, demokrasi sejati hidup bukan dari diam, melainkan dari keberanian rakyat untuk menegur. Jeritan “Bubarkan DPR” adalah bukti bahwa demokrasi kita masih bernapas, meski dengan nadi yang lemah.
Sebab kedaulatan bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk, melainkan milik mereka yang berdiri di jalanan, menuntut keadilan dengan suara serak.
Editor Redaksi nusadaily.id/*