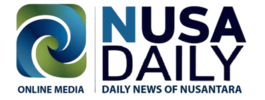Oleh: Angga Saputra, S.Pd
REDAKSI, NUSADAILY.ID – Pendidikan di Indonesia kerap dielu-elukan sebagai jalan emas menuju masa depan. Namun di balik retorika itu, wajah pendidikan kita masih jauh dari adil dan merdeka. Di kota, sekolah berfasilitas digital dengan akses global kian berkembang, sementara di pelosok negeri ribuan sekolah masih berjuang dengan ruang reyot, guru terbatas, bahkan listrik yang tak selalu menyala. Ironisnya, jurang kesenjangan ini terus melebar di tengah jargon “Merdeka Belajar” yang semakin terdengar seperti slogan politik ketimbang kenyataan.
Pendidikan sebagai Komoditas Politik
Ada yang mendasar salah dalam sistem pendidikan kita. Alih-alih menjadi ruang pembebasan, pendidikan justru sering terjebak dalam pusaran birokrasi dan tarik-menarik politik. Setiap pergantian rezim dan menteri seakan menjadi alasan untuk mengutak-atik kurikulum. Laporan World Bank (2013) mencatat bahwa reformasi guru di Indonesia kerap lebih ditentukan oleh dinamika politik ketimbang kajian akademik yang matang. Akibatnya, sekolah-sekolah berubah menjadi laboratorium percobaan bagi ambisi elite.
Jurang Antara Idealisme dan Realitas
Profil Pelajar Pancasila terdengar megah di atas kertas. Namun UNICEF (2020) menunjukkan fakta sebaliknya: masih banyak anak di pedalaman yang kesulitan mengakses pendidikan dasar. OECD (2015) menambahkan, disparitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Jika di kota siswa terbiasa dengan akses internet, di desa bahkan jalan menuju sekolah masih berlumpur dan jauh.
Guru yang Terpinggirkan
Guru, yang mestinya menjadi penggerak pendidikan, justru sering diposisikan hanya sebagai pelaksana administrasi. Mereka terjebak dalam laporan, formulir, dan aturan birokratis. Padahal, sebagaimana diingatkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), pendidik sejati adalah fasilitator dialog dan kesadaran kritis, bukan sekadar pegawai yang menjalankan perintah dari atas.
Orientasi Kognitif dan Budaya Hafalan
Orientasi pendidikan kita masih didominasi aspek kognitif: angka ujian, hafalan, dan sertifikasi. Ivan Illich dalam Deschooling Society (1971) menyebut sekolah sebagai institusi yang menciptakan kepatuhan, bukan kemandirian. Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia: ijazah lebih dihargai daripada kompetensi nyata, ranking lebih penting daripada keterampilan hidup, dan sekolah elit hanya bisa diakses oleh segelintir orang berduit.
Pendidikan dan Dunia Kerja yang Tak Bertemu
Lulusan SMA dan SMK banyak yang bingung melangkah karena sekolah gagal memberi bekal keterampilan hidup. Laporan ILO (2020) menegaskan adanya mismatch antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Henry Giroux (2004) menekankan, pendidikan seharusnya mempersiapkan warga kritis, bukan hanya buruh patuh. Peter McLaren (2015) bahkan menyerukan perlunya pedagogi insurrektional pendidikan yang mampu menyalakan kemarahan kritis demi transformasi sosial.
Jalan Pembebasan: Dari Retorika ke Aksi
Jika kita jujur, pendidikan Indonesia masih terjebak dalam logika pembangunan yang mekanistis, belum menyentuh esensi humanis-transformasional. Lulusan kita mahir mengejar nilai, namun miskin nilai kemanusiaan; terampil menghafal, tetapi gagap membaca realitas sosial. Karena itu, langkah advokatif yang mendesak ialah:
- Desentralisasi Pedagogi: Memberi ruang bagi komunitas lokal, sekolah alternatif, dan pendidikan berbasis budaya.
- Redistribusi Akses: Negara wajib menutup jurang fasilitas desa-kota melalui kebijakan afirmatif berbasis data.
- Reformasi Kurikulum: Menggeser orientasi dari kognitif-instrumental menuju pembentukan manusia kritis, merdeka, dan berdaya.
- Penguatan Guru sebagai Subjek: Guru perlu diperlakukan sebagai aktor intelektual, bukan birokrat mini. Perlindungan kesejahteraan dan ruang akademiknya harus dijamin.
Pendidikan sebagai Politik Harapan
Giroux menyebut pendidikan sebagai the politics of hope, politik harapan. Ia harus berfungsi sebagai janji pembebasan, bukan sekadar instrumen kompetisi global. Indonesia membutuhkan keberanian untuk membongkar ilusi pendidikan yang ada saat ini, lalu membangunnya kembali dengan paradigma yang memerdekakan, memanusiakan, dan menghidupkan harapan.
Daftar Referensi
Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed (30th Anniversary Edition). New York: Continuum. (Karya asli diterbitkan 1970).
Illich, I. (1971). Deschooling Society. New York: Harper and Row.
Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury Academic.
McLaren, P. (2015). Pedagogy of Insurrection: From Resurrection to Revolution. New York: Peter Lang.
UNESCO. (2022). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO Publishing.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar. Jakarta: Kemendikbudristek. Rahardjo, M. (2021). Krisis Pendidikan di Indonesia: Sebuah Kajian Kritis. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 15(2), 45–60.