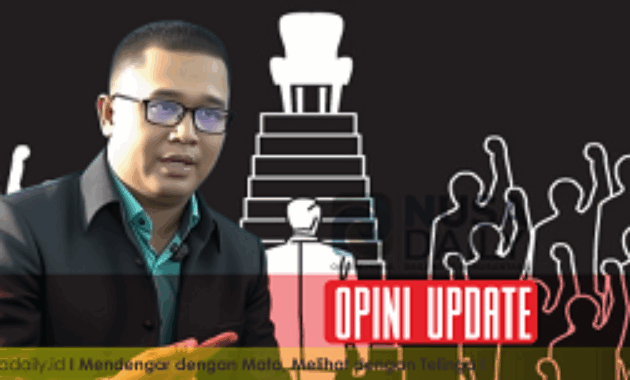Oleh : Dr. Nanang Al Hidayat
(Peneliti SDGs Center/Dosen IAK Setih Setio/Advokat Peradi)
OPINI, NUSADAILY.ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang KUHAP merupakan salah satu tonggak reformasi hukum yang menentukan arah penegakan hukum di Indonesia. Secara politik hukum, langkah ini menandai upaya pemerintah memperbarui paradigma hukum acara pidana yang selama ini dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP lama, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, telah lama dikritik karena mewarisi pola pikir kolonial dan terlalu menekankan legalisme formal, sehingga sering menghambat keadilan substantif.
Dalam proses perubahan ini, politik hukum pemerintah berangkat dari pandangan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan “kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah mengenai hukum apa yang akan dibentuk serta bagaimana hukum tersebut ditegakkan” (Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia). Karena itu, pengesahan RUU KUHAP tidak sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan pilihan kebijakan strategis untuk memperkuat due process of law, memperluas kontrol yudisial, dan menata ulang relasi kekuasaan antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
Orientasi pembaruan hukum acara pidana ini juga berakar pada mandat konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Norma ini memberikan landasan filosofis bahwa sistem peradilan pidana tidak lagi boleh bertumpu pada pola represif, melainkan harus berbasis perlindungan hak dan prinsip fair trial, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Karena itu, pembaruan KUHAP merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk memastikan proses peradilan berlangsung adil dan proporsional.
Dalam perspektif penegakan hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar mesin aturan yang kaku. Satjipto menegaskan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” (Hukum Progresif). Prinsip ini menuntut negara tidak hanya menyediakan proses peradilan yang tertib, tetapi juga membongkar paradigma lama yang memosisikan tersangka dan terdakwa sebagai objek kekuasaan negara. Dengan demikian, KUHAP baru harus mampu mengintegrasikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan transparansi sebagai roh penegakan hukum.
Sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru, seperti penguatan fungsi praperadilan, perluasan penggunaan alat bukti elektronik, kewajiban pencatatan dan digitalisasi tindakan penyidikan, serta kehadiran penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan, merupakan langkah konkret menuju penegakan hukum yang progresif. Ketentuan-ketentuan tersebut berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka maupun korban. Dengan memperkuat mekanisme kontrol terhadap tindakan koersif aparat, pemerintah berupaya mendorong terwujudnya proses peradilan pidana yang lebih akuntabel.
Namun, politik hukum tidak pernah steril dari tarik-menarik kepentingan. Di balik progresivitas KUHAP baru, muncul kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan justru dapat membuka peluang perluasan kewenangan represif negara jika tidak disertai instrumen pengawasan yang kuat. Misalnya, legalisasi penyadapan dan perluasan alat bukti elektronik berpotensi disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan kontrol yudisial yang ketat. Di sinilah relevansi teori politik hukum Soetandyo Wignjosoebroto: hukum selalu berada dalam “kontestasi kepentingan”, sehingga efektivitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh struktur kekuasaan dan kultur penegakan hukumnya.
Karena itu, pembaruan KUHAP menuntut reformasi institusional yang berjalan paralel. Pemerintah perlu memastikan implementasi undang-undang ini selaras dengan prinsip konstitusional, terutama penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pengawasan internal dan eksternal lembaga penegak hukum harus diperkuat, sistem digital harus transparan, dan pendidikan etika aparat mesti menjadi prioritas. Tanpa hal-hal tersebut, progresivitas dalam teks undang-undang hanya akan berhenti sebagai janji normatif yang tidak pernah terwujud dalam praktik.
Pada akhirnya, pengesahan RUU KUHAP menjadi UU KUHAP dapat dibaca sebagai konsolidasi arah politik hukum pemerintah menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan manusiawi. Pemerintah berupaya melepaskan diri dari paradigma kolonial yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan represif, dan bergeser menuju paradigma negara hukum modern yang melindungi hak-hak warga negara. Namun progresivitas hukum acara pidana tidak hanya bergantung pada rumusan normanya, tetapi terutama pada pelaksanaannya. Sebagaimana ditegaskan Gustav Radbruch, “keadilan dan kemanfaatan hukum tidak dapat sepenuhnya dicapai hanya melalui teks, tetapi melalui interpretasi yang adil oleh para penegak hukum.”
Dengan demikian, KUHAP baru merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan reformasi peradilan pidana tetap bergantung pada komitmen aparat penegak hukum untuk menjalankan prinsip due process, integritas etis, dan keberpihakan pada keadilan substantif. Politik hukum yang progresif hanya dapat terwujud apabila teks undang-undang diterjemahkan secara konsisten menjadi praktik penegakan hukum yang manusiawi, akuntabel, dan sesuai dengan nilai konstitusi.
Redaksi nusadaily.id/*