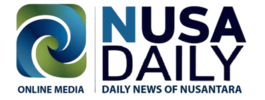Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
JAMBI, NUSADAILY.ID – Tulisan ini sengaja saya sampaikan untuk menjawab klaim PT SAS menyampaikan bahwa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Aur Kenali akan menerapkan arsitektur hijau dan teknologi adaptif untuk menekan debu serta kebisingan, argumentasi tersebut menyisakan sejumlah catatan kritis yang perlu dicermati secara ilmiah, hukum, ekonomi-politik, dan kesehatan masyarakat.
Pertama, pengalaman di berbagai wilayah pengoperasian TUKS batubara di Indonesia menunjukkan bahwa klaim pengendalian dampak lingkungan kerap berbeda dengan realitas lapangan. Conveyor tertutup dan dust suppression memang dapat menekan emisi partikulat, namun tidak sepenuhnya menghilangkan potensi debu batubara yang bisa terbawa angin terutama di area stockpile terbuka (Putra et al., 2021).
Kedua, ruang terbuka hijau seluas 62 hektar yang diklaim dapat menyerap polutan dan meredam kebisingan belum tentu efektif. Penelitian menunjukkan efektivitas vegetasi sangat ditentukan oleh jarak, kepadatan, dan orientasi tanaman terhadap sumber polusi. Tanpa tata letak yang tepat, fungsi ruang hijau lebih bersifat simbolis daripada substantif (Fahrudin & Sari, 2020).
Ketiga, klaim bahwa tidak adanya aktivitas crushing di TUKS akan meniadakan kebisingan dan debu juga problematis. Aktivitas bongkar muat batubara, pergerakan truk, serta operasi conveyor tetap menimbulkan kebisingan dan getaran signifikan. Studi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022) mencatat bahwa kebisingan di kawasan pelabuhan batubara sering melampaui baku mutu, terutama jika dekat dengan pemukiman. Aur Kenali sendiri merupakan kawasan dengan pemukiman padat, sehingga risiko gangguan kesehatan akibat paparan debu PM2.5 dan PM10 tidak dapat diabaikan.
Keempat, penggunaan sistem penyemprotan air (dust suppression system) yang disebutkan PT SAS justru menimbulkan potensi persoalan baru. Sistem ini membutuhkan ketersediaan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Di tengah isu keterbatasan pasokan air bersih di beberapa wilayah Jambi, pemanfaatan air secara masif untuk operasional tambang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya air (Fitriani, 2023).
Dari aspek hukum, klaim PT SAS bahwa semua rencana telah dituangkan dalam dokumen AMDAL tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum yang lebih luas. Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL. Namun, Pasal 22 dan 23 undang-undang yang sama menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Jika proses partisipasi publik minim atau hanya formalitas, maka dokumen AMDAL dapat dipersoalkan secara hukum.
Lebih jauh, Pasal 69 ayat (1) huruf e UU No. 32/2009 melarang kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan potensi timbulnya kebisingan, debu, dan risiko penurunan kualitas udara, TUKS Aur Kenali tetap berpeluang melanggar prinsip kehati-hatian lingkungan (precautionary principle) yang telah menjadi asas hukum lingkungan di Indonesia.
Dari perspektif ekonomi-politik, keberadaan TUKS Aur Kenali lebih banyak melayani kepentingan industri batubara ketimbang masyarakat sekitar. Pembangunan jalan khusus batubara, terminal bongkar muat, hingga klaim arsitektur hijau pada dasarnya adalah strategi untuk memperlancar rantai pasok komoditas ekspor. Sementara itu, manfaat ekonomi bagi warga sekitar sangat terbatas, terutama jika dibandingkan dengan beban lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat. Menurut kajian Wijayanto (2022), model pembangunan ekstraktif berbasis batubara di Jambi cenderung memperdalam ketergantungan daerah terhadap sektor primer yang rentan, serta meminggirkan sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Ketidakadilan distribusi manfaat ini juga sejalan dengan teori resource curse, di mana daerah kaya sumber daya justru mengalami stagnasi pembangunan karena kebijakan lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar ketimbang kepentingan masyarakat luas (Auty, 2001). Dalam konteks Jambi, proyek TUKS Aur Kenali seharusnya ditinjau kembali bukan hanya dari aspek teknis dan AMDAL, tetapi juga dari sudut keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan arah transisi energi nasional.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, kehadiran TUKS Aur Kenali dengan aktivitas bongkar-muat batubara, stockpile, pergerakan truk berat, dan operasional conveyor menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang nyata dan terukur. Paparan partikel halus (terutama PM2.5 dan PM10) dari coal handling dapat menyebabkan dan memperburuk berbagai penyakit pernapasan dan kardiovaskular, termasuk ISPA, asma, bronkitis kronis, PPOK, hingga peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke (WHO, 2021; WHO, 2024).
Studi menunjukkan bahwa debu dari aktivitas pertambangan mengandung fraksi respirabel yang mampu masuk ke alveoli paru dan memicu inflamasi kronis. Paparan jangka panjang dikaitkan dengan pneumokoniosis (black lung disease) dan gangguan fungsi paru permanen (Kamanzi et al., 2023; Akbar et al., 2024). Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi. Penelitian WHO juga mengaitkan paparan PM2.5 dengan komplikasi kehamilan dan dampak neurologis pada janin dan anak.
Kasus-kasus lokal di Indonesia memperlihatkan pengalaman buruk ketika stockpile dan operasi pelabuhan batubara berdampingan dengan permukiman: keluhan ISPA meningkat, kualitas udara menurun, dan produktivitas warga terganggu (Mongabay, 2020). Kajian Energy & Clean Air (2022) untuk PLTU/TUKS Jambi juga menekankan bahwa tanpa kontrol ketat dan pemantauan independen, beban kesehatan dan biaya eksternalitas bagi masyarakat bisa signifikan.
Dengan demikian, klaim PT SAS bahwa TUKS Aur Kenali sepenuhnya ramah lingkungan dan minim dampak patut dipertanyakan. Dari sisi ekologi, hukum, ekonomi-politik, dan kesehatan masyarakat, proyek ini berpotensi lebih banyak menghadirkan risiko daripada manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jambi.
Daftar Pustaka
Auty, R. (2001). Resource Abundance and Economic Development. Oxford: Oxford University Press.
Fahrudin, A., & Sari, D. (2020). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Polutan Udara dan Mereduksi Kebisingan di Kawasan Perkotaan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(2), 85–98.
Fitriani, R. (2023). Konflik Pemanfaatan Air Bersih di Daerah Pertambangan: Studi Kasus Jambi. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 10(1), 33–42.
Hidayat, A. (2019). Problematika Implementasi AMDAL dalam Industri Ekstraktif di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 456–478.
Kamanzi, C., et al. (2023). The impact of coal mine dust characteristics on pathways to pneumoconiosis and other diseases. Environmental Health.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Laporan Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Batubara. Jakarta: KLHK.
Mongabay. (2020). Coal stockpiles threaten public health in Indonesia. Jakarta: Mongabay Indonesia.
Putra, Y., Nugroho, B., & Wijayanti, E. (2021). Dampak Operasional Stockpile Batubara terhadap Kualitas Udara di Kawasan Pesisir. Jurnal Teknologi Lingkungan, 22(1), 45–57.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Wijayanto, H. (2022). Ekonomi Politik Pertambangan Batubara di Jambi: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Krisis Sosial-Lingkungan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 71–89.
World Health Organization. (2021). WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM2.5 and PM10), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide — Executive Summary. Geneva: WHO. World Health Organization. (2024). Ambient (outdoor) air quality and health — Fact sheet. Geneva: WHO.