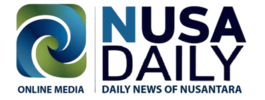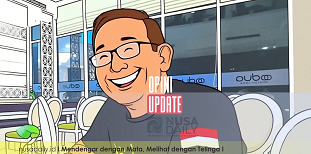Oleh: Budi Prasetiyo
BUNGO, NUSADAILY.ID – Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 731 Tahun 2025 patut diapresiasi. Langkah mundur yang ditempuh Ketua KPU, Afifuddin, dengan alasan “mendengarkan aspirasi publik” membuktikan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan. Namun, langkah itu justru menguak masalah yang lebih fundamental: betapa roh demokrasi, yakni keterbukaan, masih rentan digerogoti dari dalam.
Keputusan awal KPU yang membatasi akses publik terhadap 16 jenis dokumen, termasuk ijazah calon presiden dan wakil presiden, bukan sekadar kesalahan administratif. Itu adalah pelanggaran prinsipil terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kritik deras dari anggota DPR lintas fraksi, mulai dari PDIP, Demokrat, Golkar, hingga NasDem, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan ini telah melukai konsensus dasar tentang tata kelola pemilu yang transparan.
Masyarakat sipil, melalui Perludem, juga menyuarakan dengan sangat tepat: pembatasan informasi publik adalah pencabutan hak konstitusional rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dapat menjalankan kedaulatannya dengan bijak jika mereka dibutakan dari jati diri calon pemimpinnya? Transparansi bukanlah sebuah kemewahan; ia adalah fondasi untuk membangun kepercayaan (trust), modal sosial terpenting dalam setiap proses demokrasi.
Yang paling mengusik justru adalah timing-nya yang janggal. Pemilu presiden 2024 telah usai, sementara pilpres berikutnya masih empat tahun mendatang. Apa yang mendasari kebutuhan untuk menutup informasi justru di masa antar-waktu ini? Kecurigaan publik bahwa ada motif tersembunyi di balik kebijakan tersebut merupakan respons yang wajar dan logis. Situasi ini semakin menegaskan peran vital DPR, masyarakat sipil, dan media sebagai pilar pengawas demokrasi yang harus terus menjaga KPU agar konsisten pada jalur konstitusionalnya.
Di sinilah peran media tidak boleh berhenti pada pemberitaan soal pembatalan. Tugas jurnalistik yang sesungguhnya justru dimulai sekarang: mengungkap akar persoalan. Siapa aktor di balik wacana pembatasan ini? Bagaimana sebuah kebijakan yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip keterbukaan bisa lolos dari rapat pleno KPU? Investigasi mendalam mutlak diperlukan untuk membongkar proses pengambilan keputusan yang kelam ini, sekaligus memastikan ia tidak terulang di masa depan.
Pembatalan keputusan ini adalah koreksi, tetapi bukan kejayaan. Ia hanyalah pengakuan bahwa sebuah kesalahan fatal hampir terjadi. Demokrasi tidak bisa hidup dalam ruang yang gelap; ia membutuhkan cahaya keterbukaan untuk tumbuh. Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya diukur pada hari pencoblosan, melainkan juga pada sejauh mana akses informasi yang setara diberikan kepada publik untuk membuat keputusan rasional.
Oleh karena itu, perjalanan ini belum usai. Publik berhak tahu alasan di balik kesalahan tersebut. KPU harus membuka diri, tidak hanya dengan membatalkan keputusan, tetapi juga menjelaskan secara transparan proses yang menyebabkan lahirnya keputusan kontroversial itu. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Demokrasi dibangun dengan data dan keterbukaan, bukan dengan dugaan dan kecurigaan. Tugas kita bersama adalah memastikan jiwa keterbukaan tetap hidup dalam setiap denyut nadi penyelenggaraan pemilu.
Redaksi nusadaily.id/*