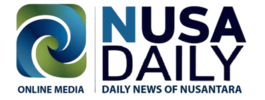Oleh: Dr. Nanang Al Hidayat (Peneliti SDGs Center/Dosen IAKSS/Advokat Peradi)
BUNGO, NUSADAILY.ID – Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) menandai sebuah fase penting dalam perjalanan hukum Indonesia. Gagasan besar dari RUU ini adalah memperkuat instrumen hukum dalam memberantas kejahatan ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, dengan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga merampas hasil kejahatan yang mereka nikmati. Seperti ditegaskan oleh pemerintah, “RUU ini diharapkan menjadi senjata baru negara dalam memutus mata rantai kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat” (Kompas, 2024).
Kelebihan yang paling menonjol dari RUU ini adalah keberanian mengadopsi mekanisme non conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Dengan mekanisme ini, negara dapat tetap merampas aset meskipun terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan. Hal ini menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk melindungi aset mereka dari jangkauan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu naskah akademik RUU, “kerugian negara tidak boleh berhenti hanya karena pelaku lolos dari jeratan pidana” (DPR RI, 2023).
Dari sudut pandang publik, keberadaan RUU ini juga membawa harapan akan hadirnya keadilan yang lebih substantif. Hukuman tidak lagi berhenti pada badan pelaku, tetapi meluas hingga ke hasil kejahatan. Masyarakat dapat melihat bahwa aset yang sejatinya diperoleh secara melawan hukum akhirnya kembali kepada negara. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana, Todung Mulya Lubis, yang menegaskan bahwa “hukuman yang hanya memenjarakan orang tanpa menyentuh hasil kejahatan adalah setengah hati dan tidak memberikan efek jera” (Lubis, 2022).
Kelebihan lainnya adalah penyesuaian Indonesia dengan standar global. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) secara eksplisit mendorong negara-negara pihak untuk mengadopsi instrumen hukum pemulihan aset (asset recovery). Dengan mengesahkan RUU ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak menjadi surga aman bagi aset hasil kejahatan lintas negara. Hal ini juga menguatkan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional melawan korupsi dan kejahatan transnasional.
Namun, kelebihan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Justru dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, terdapat kerentanan serius. Mekanisme non conviction based forfeiture berpotensi melanggar asas due process of law dan prinsip presumption of innocence. Seperti dikritik oleh sejumlah akademisi, “perampasan aset tanpa putusan pidana membuka ruang bagi negara untuk merampas hak milik seseorang sebelum ia terbukti bersalah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas kepemilikan” (Kompas, 2024).
Masalah lain muncul dari formulasi norma yang masih kabur. RUU ini menggunakan istilah “aset yang tidak wajar” atau “kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya”. Frasa ini membuka ruang tafsir yang luas dan menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi sangat dominan untuk menentukan apakah suatu kekayaan layak dirampas atau tidak. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih bergulat dengan problem integritas aparat, kekhawatiran akan moral menjadi sangat nyata. Seorang anggota Komisi III DPR bahkan menegaskan, “jangan sampai aturan ini menjadi pedang bermata dua, yang tidak hanya mengenai penjahat ekonomi tetapi juga masyarakat biasa yang tidak paham bagaimana membuktikan asal usul kekayaannya” (DPR, 2024).
Potensi tumpang tindih hukum juga tidak dapat dihindari. RUU Perampasan Aset harus bersinergi dengan KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Tanpa sinkronisasi, justru akan lahir ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Inkonsistensi prosedural antara undang-undang bisa menimbulkan dualisme, misalnya ketika satu perkara diadili dengan KUHAP sementara perampasan asetnya berjalan dengan aturan khusus. Situasi ini tidak hanya berisiko melemahkan kepastian hukum, tetapi juga dapat memicu uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, mekanisme pembuktian terbalik yang kemungkinan diatur dalam RUU ini menimbulkan dilema. Beban bagi pemilik aset untuk membuktikan keabsahan kekayaannya seringkali lebih berat dibandingkan dengan kapasitas aparat penegak hukum untuk membuktikan dugaan kejahatan. Kondisi ini bisa merugikan warga negara yang jujur namun tidak mampu menghadirkan dokumen atau bukti karena faktor waktu, kerusakan arsip, atau sebab lain. Kritik ini senada dengan pernyataan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, yang mengatakan bahwa “RUU ini harus hati-hati dalam menempatkan beban pembuktian, sebab jika terlalu berat pada warga, justru negara yang melanggar prinsip keadilan” (Kompas, 2024).
Menyadari kelebihan dan kekurangannya, diperlukan sejumlah rekomendasi agar RUU ini tidak menjadi instrumen yang menakutkan masyarakat. Pertama, definisi hukum mengenai aset yang dapat dirampas harus jelas dan tegas, sehingga tidak membuka ruang tafsir berlebihan. Kedua, perampasan aset harus selalu melalui mekanisme peradilan dengan pengawasan yudisial yang ketat untuk memastikan due process tetap terjaga. Ketiga, sinkronisasi dengan undang-undang lain wajib dilakukan agar tidak menimbulkan kontradiksi. Keempat, aparat penegak hukum harus diperkuat kapasitasnya, baik dari segi integritas maupun keahlian dalam investigasi aset. Tanpa itu, instrumen hukum ini bisa berubah menjadi alat represi yang kontraproduktif.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi instrumen ampuh untuk menutup ruang gerak kejahatan ekonomi, mengembalikan kepercayaan publik, dan memenuhi kewajiban internasional. Tetapi di sisi lain, jika tidak dirumuskan secara hati-hati, ia justru bisa melukai sendi konstitusional negara hukum dengan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU ini harus dilakukan secara mendalam, partisipatif, dan berbasis kajian akademik yang kuat. Seperti diingatkan oleh seorang anggota masyarakat sipil, “kita butuh undang-undang yang kuat untuk melawan korupsi, tapi bukan undang-undang yang melawan rakyat”.
Redaksi nusadaily.id/*